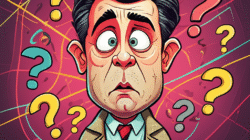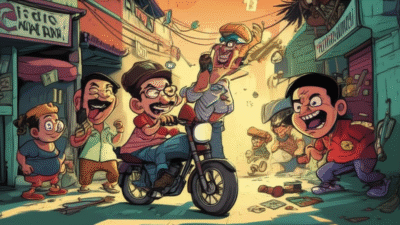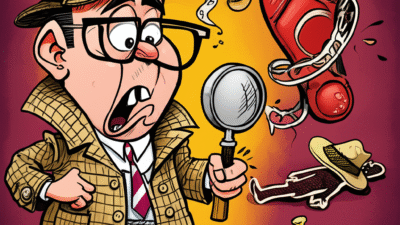Dinamika Premanisme Terminal: Membongkar Lapisan Kekuasaan, Kebutuhan, dan Ketertiban Semu di Gerbang Kota
Terminal bus, sebagai gerbang utama bagi mobilitas manusia dan barang di perkotaan, seringkali digambarkan sebagai miniatur masyarakat yang kompleks. Di dalamnya, berinteraksi beragam lapisan sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, di balik hiruk pikuk transaksi tiket, deru mesin bus, dan lalu lalang penumpang, terselip sebuah bayangan yang kerap kali memicu ketakutan dan ketidaknyamanan: fenomena premanisme. Premanisme terminal bukan sekadar label bagi individu-individu bertampang sangar, melainkan sebuah ekosistem rumit yang berakar pada sejarah, kondisi sosial-ekonomi, dan dinamika kekuasaan yang tak tertulis. Artikel ini akan membongkar lapisan-lapisan tersebut, memahami mengapa premanisme tetap eksis, bagaimana strukturnya bekerja, serta dampaknya terhadap wajah terminal sebagai pusat transportasi publik.
Definisi dan Stigma: Lebih dari Sekadar Kekerasan
Secara harfiah, "preman" berasal dari bahasa Belanda "vrijman" yang berarti "orang bebas" atau "orang merdeka". Namun, dalam konteks Indonesia, istilah ini telah mengalami pergeseran makna drastis, merujuk pada individu atau kelompok yang mengklaim kekuasaan atau pengaruh di suatu wilayah, seringkali melalui intimidasi, kekerasan, atau pemerasan. Di terminal, preman identik dengan pungutan liar (pungli), calo tiket ilegal, pengatur parkir tanpa izin, hingga pelaku tindak kriminal ringan seperti pencopetan atau penipuan.
Stigma yang melekat pada preman terminal adalah citra negatif yang tunggal: sosok pembuat onar, parasit yang meresahkan. Namun, pandangan ini terlalu menyederhanakan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa ada spektrum peran dan motif yang lebih luas. Ada preman yang murni kriminal, namun ada pula yang melihat diri mereka sebagai "penjaga" atau "pengatur" ketimbang perampok, bahkan ada yang merupakan korban dari sistem yang lebih besar. Memahami premanisme berarti melihat di balik fasad kekerasan, mencari akar masalah dan fungsi-fungsi tersembunyi yang mungkin mereka penuhi dalam kekosongan sistem.
Akar Historis dan Sosial-Ekonomi: Mengapa Preman Bermunculan?
Kemunculan premanisme di terminal tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah dan kondisi sosial-ekonomi Indonesia. Pasca-kemerdekaan dan di era Orde Baru, urbanisasi besar-besaran terjadi. Banyak masyarakat desa yang miskin dan tak punya keahlian khusus hijrah ke kota dengan harapan mencari nafkah. Namun, lapangan pekerjaan formal yang terbatas membuat mereka terpaksa mencari penghidupan di sektor informal, termasuk di terminal.
Celah-celah kekuasaan dan regulasi yang lemah di terminal menjadi lahan subur bagi pembentukan kelompok-kelompok informal yang menguasai wilayah. Pemerintah atau aparat keamanan belum sepenuhnya mampu mengendalikan setiap sudut terminal, menciptakan "kekosongan" yang kemudian diisi oleh mereka yang berani mengambil alih. Kondisi ini diperparah oleh:
- Kemiskinan dan Pengangguran: Mayoritas individu yang terlibat dalam premanisme berasal dari latar belakang ekonomi lemah, tanpa akses pendidikan atau keterampilan memadai. Bagi mereka, menjadi preman seringkali adalah pilihan terakhir untuk bertahan hidup, menawarkan "pekerjaan" dan "penghasilan" yang tidak bisa mereka dapatkan di tempat lain.
- Jejaring Sosial dan Solidaritas: Dalam kondisi sulit, kelompok-kelompok ini menawarkan rasa memiliki, identitas, dan solidaritas yang mungkin tidak mereka temukan di masyarakat formal. Mereka membangun "keluarga" di jalanan, dengan aturan dan kode etik internal yang unik.
- Lemahnya Penegakan Hukum: Kerap kali, aparat hukum kesulitan memberantas premanisme secara tuntas. Penangkapan seringkali bersifat temporer, dan akar masalahnya tidak tersentuh. Bahkan, dalam beberapa kasus, terjadi kolusi antara preman dengan oknum aparat, menciptakan siklus yang sulit diputus.
- Budaya Kekerasan: Di lingkungan yang keras, kekerasan menjadi alat komunikasi dan penentu status. Kemampuan untuk menekan atau mengintimidasi menjadi modal sosial untuk bertahan dan mendapatkan penghasilan.
Anatomi Kekuasaan: Struktur dan Cara Kerja Preman Terminal
Premanisme di terminal tidak selalu bersifat acak atau sporadis. Di banyak tempat, ada struktur dan hierarki yang jelas, meskipun tidak tertulis secara formal. Mereka menguasai "wilayah" tertentu di terminal, seperti area parkir, pintu masuk/keluar, loket penjualan tiket, atau area bongkar muat barang.
- Pimpinan dan Anak Buah: Ada "bos" atau "koordinator" yang mengatur anak buahnya. Bos ini biasanya adalah figur lama yang memiliki pengaruh dan koneksi, sementara anak buah adalah pelaksana di lapangan.
- Pembagian Tugas: Anggota preman memiliki peran masing-masing:
- Calo Tiket: Memaksa penumpang membeli tiket dengan harga lebih tinggi atau memanipulasi informasi ketersediaan kursi.
- Pengatur Parkir Ilegal: Memungut biaya parkir di luar ketentuan resmi, seringkali dengan ancaman.
- Pungli: Meminta uang keamanan atau uang rokok dari sopir bus, kondektur, pedagang asongan, atau bahkan penumpang, dengan dalih "menjaga" atau "mengamankan".
- "Jaga Keamanan": Paradoxically, sebagian preman juga berfungsi sebagai "penjaga keamanan" informal. Mereka mungkin mencegah pencopetan dari kelompok lain, atau menyelesaikan perselisihan kecil di antara pedagang, tentu saja dengan imbalan.
- Penadah dan Pengedar: Beberapa kelompok juga terlibat dalam aktivitas ilegal yang lebih serius seperti penadahan barang curian atau pengedaran narkoba skala kecil.
- Mekanisme Kontrol: Mereka menjaga "ketertiban" di wilayah mereka melalui intimidasi, ancaman, dan sesekali kekerasan fisik. Siapa pun yang menolak membayar atau menentang aturan mereka akan menghadapi konsekuensi.
- Jaringan Informasi: Preman memiliki jaringan informasi yang luas di terminal. Mereka tahu kapan bus tiba, siapa penumpang yang terlihat kaya, atau kapan ada operasi penertiban. Informasi ini menjadi modal penting dalam menjalankan aktivitas mereka.
Dua Sisi Mata Uang: Fungsi Ganda yang Kontroversial
Meskipun identik dengan kekerasan dan kejahatan, premanisme di terminal juga seringkali dianggap memiliki fungsi ganda yang kontroversial, bahkan oleh sebagian pihak yang terpaksa berinteraksi dengan mereka:
-
Sisi Negatif (yang dominan):
- Merusak Citra Terminal: Menciptakan suasana tidak aman dan tidak nyaman bagi penumpang dan pengunjung.
- Kerugian Ekonomi: Pungutan liar meningkatkan biaya operasional bagi pengusaha bus dan harga barang bagi pedagang, yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen.
- Tindakan Kriminal: Pencopetan, penipuan, pemerasan, hingga kekerasan fisik.
- Menghambat Pembangunan: Keberadaan premanisme mempersulit upaya pemerintah untuk menata dan mengembangkan terminal menjadi lebih modern dan tertib.
-
Sisi Ambigu/Fungsional (dari perspektif internal atau pihak yang bergantung):
- Penyedia "Keamanan" Informal: Dalam kekosongan penegakan hukum yang efektif, preman kadang mengisi peran sebagai "penjaga" wilayah. Sopir bus atau pedagang mungkin merasa "lebih aman" setelah membayar pungli, karena mereka tahu preman lain tidak akan mengganggu. Ini adalah bentuk ketertiban semu yang dibangun di atas rasa takut.
- Penyelesaian Konflik: Preman juga bisa berperan sebagai mediator atau penengah dalam perselisihan antar pedagang, sopir, atau bahkan penumpang, menggunakan otoritas mereka untuk menyelesaikan masalah tanpa melibatkan aparat resmi.
- Penyerap Tenaga Kerja Informal: Bagi individu yang tidak punya pilihan lain, kelompok premanisme bisa menjadi "lapangan kerja" dan sumber penghidupan, memberikan mereka identitas dan tujuan.
- Jaringan Sosial: Mereka membentuk jaringan sosial yang kuat, saling membantu di antara anggota, bahkan di luar aktivitas premanisme.
Dinamika Hubungan dengan Pihak Lain: Kompleksitas Interaksi
Hubungan antara preman terminal dengan berbagai pihak sangatlah kompleks dan dinamis:
- Dengan Aparat Keamanan: Hubungan ini bersifat tarik-ulur. Ada operasi penertiban yang gencar, namun tak jarang pula ditemukan pola-pola akomodatif, bahkan kolusi. Seringkali, penangkapan hanya menyasar "anak buah" sementara "bos" tetap bersembunyi atau bahkan dilindungi.
- Dengan Pengusaha Transportasi (PO Bus, Sopir, Kondektur): Mereka adalah "korban" utama pungli. Namun, mereka juga seringkali terpaksa "bekerja sama" atau "mengakomodasi" preman demi kelancaran operasional dan keamanan. Membayar sejumlah uang dianggap sebagai "biaya operasional" untuk menghindari masalah yang lebih besar.
- Dengan Pedagang dan Pekerja Informal Lain: Mirip dengan pengusaha transportasi, mereka juga sering menjadi sasaran pungli. Namun, beberapa pedagang juga menjalin hubungan "baik" dengan preman untuk mendapatkan "perlindungan" dari preman lain atau pesaing.
- Dengan Masyarakat/Penumpang: Masyarakat umum adalah pihak yang paling dirugikan dan merasa takut. Mereka menghindari konfrontasi dan sebisa mungkin mempercepat keberangkatan untuk menghindari interaksi.
Upaya Penanganan dan Tantangan: Mencari Solusi Berkelanjutan
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi premanisme terminal, mulai dari razia rutin, penangkapan massal, hingga program pembinaan. Namun, hasilnya seringkali temporer. Premanisme adalah masalah yang berakar dalam, dan solusi pun harus komprehensif:
- Penegakan Hukum yang Konsisten dan Bersih: Tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga membongkar jaringan yang lebih besar, termasuk oknum yang melindungi mereka. Ini memerlukan komitmen kuat dan integritas dari aparat.
- Penataan Sistem Terminal: Membuat sistem operasional terminal yang lebih transparan, modern, dan tidak meninggalkan celah bagi praktik pungli dan percaloan. Penggunaan teknologi (misalnya, tiket elektronik) dapat sangat membantu.
- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Memberikan pelatihan keterampilan dan akses ke lapangan kerja formal bagi individu-individu yang rentan terhadap premanisme. Ini adalah solusi jangka panjang yang paling efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan yang menjadi akar masalah.
- Reintegrasi Sosial: Memberikan program rehabilitasi dan pembinaan bagi mantan preman agar mereka dapat kembali diterima di masyarakat dan memiliki penghidupan yang layak.
- Edukasi Publik: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai pengguna terminal dan pentingnya melaporkan tindakan premanisme tanpa rasa takut.
- Kolaborasi Multi-Pihak: Pemerintah, aparat keamanan, pengusaha, masyarakat sipil, dan komunitas lokal harus bekerja sama secara sinergis untuk menciptakan lingkungan terminal yang aman, tertib, dan inklusif.
Kesimpulan
Premanisme di terminal adalah fenomena sosial yang kompleks, bukan sekadar masalah kriminalitas semata. Ia adalah cerminan dari ketimpangan ekonomi, kelemahan sistem, dan dinamika kekuasaan informal yang tumbuh di celah-celah masyarakat urban. Memahami premanisme berarti melihatnya sebagai sebuah ekosistem dengan akar historis, struktur internal, dan fungsi-fungsi ganda yang kontroversial.
Pemberantasan premanisme secara tuntas tidak cukup hanya dengan pendekatan represif. Ia membutuhkan solusi holistik yang menyentuh akar masalah: meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memperkuat penegakan hukum yang bersih, menata sistem transportasi publik secara transparan, dan memberdayakan masyarakat. Hanya dengan pendekatan multi-dimensi ini, bayangan premanisme dapat secara perlahan memudar, dan terminal dapat sepenuhnya menjadi gerbang kota yang aman, nyaman, dan berfungsi optimal bagi seluruh masyarakat.