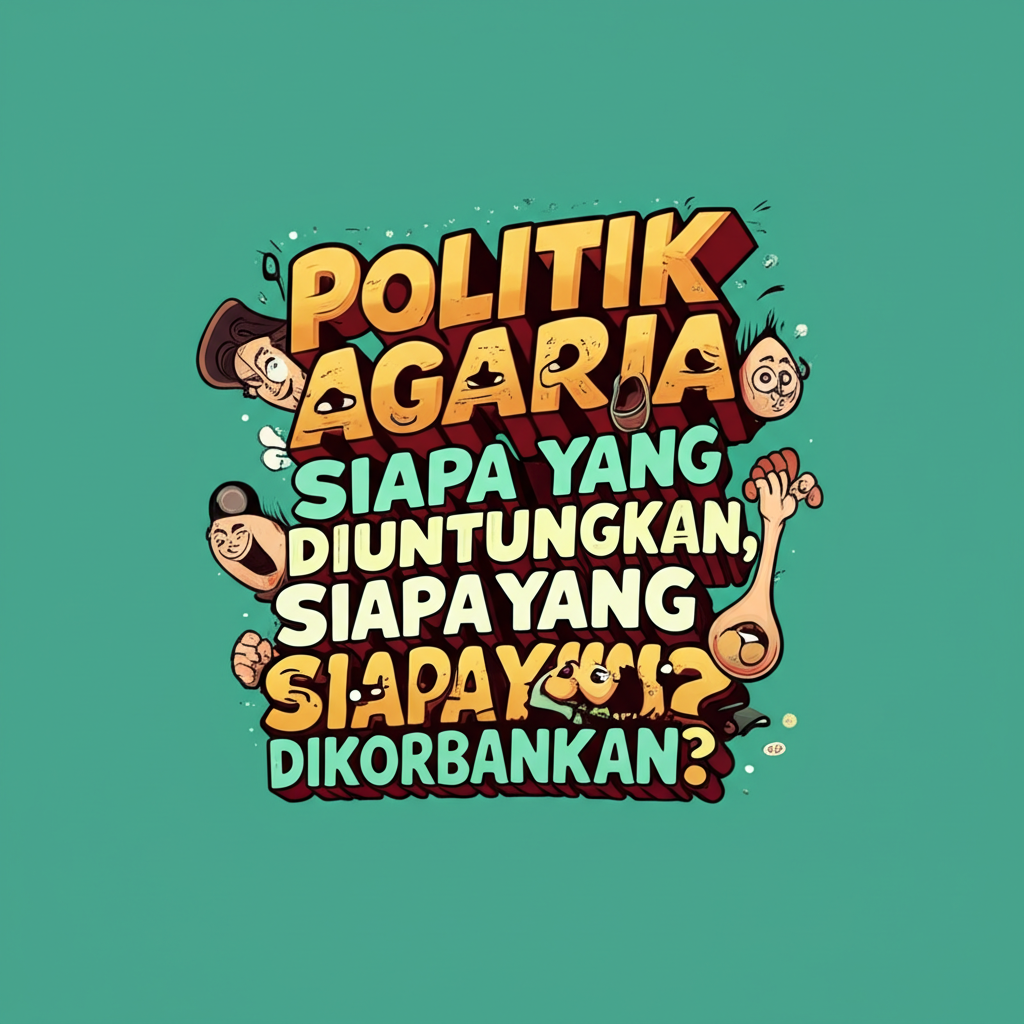Politik Agraria: Siapa yang Diuntungkan, Siapa yang Dikorbankan?
Politik agraria adalah jantung dari pertarungan kekuasaan dan keadilan di banyak negara, terutama di Indonesia. Ia bukan sekadar tentang tanah, melainkan tentang penguasaan, pemanfaatan, dan distribusi sumber daya yang paling fundamental bagi kehidupan manusia. Di balik setiap kebijakan pertanahan, perizinan perkebunan, atau proyek infrastruktur raksasa, tersembunyi sebuah narasi kompleks tentang siapa yang meraup keuntungan dan siapa yang harus menanggung beban penderitaan. Artikel ini akan mengurai dinamika politik agraria yang kerap memihak segelintir pihak, sementara mengorbankan jutaan lainnya, serta implikasinya terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
1. Definisi dan Konteks Politik Agraria
Politik agraria dapat dipahami sebagai arena di mana kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan politik berinteraksi untuk membentuk kebijakan dan praktik terkait kepemilikan, akses, penggunaan, dan kontrol atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Ini mencakup hukum, regulasi, institusi, serta hubungan kekuasaan yang menentukan siapa yang berhak atas tanah, untuk tujuan apa, dan bagaimana konflik atas tanah diselesaikan. Di Indonesia, sejarah politik agraria sangat kental dengan warisan kolonial yang mengedepankan eksploitasi sumber daya, dan pasca-kemerdekaan, dinamika ini terus berlanjut, seringkali dengan wajah yang berbeda namun esensi yang sama.
Tanah, dalam konteks agraria, bukan hanya sebidang lahan fisik. Bagi masyarakat adat dan petani tradisional, tanah adalah identitas, sumber mata pencaharian, warisan leluhur, dan fondasi spiritual. Namun, dalam kacamata ekonomi modern, tanah seringkali direduksi menjadi komoditas, aset yang bisa diperdagangkan, atau faktor produksi yang dieksploitasi untuk keuntungan maksimal. Pergeseran paradigma inilah yang menjadi pemicu utama konflik dan ketimpangan.
2. Siapa yang Diuntungkan? Hegemoni Korporasi dan Negara (dalam Bentuk Tertentu)
Dalam lanskap politik agraria kontemporer, aktor-aktor besar yang memiliki modal, kekuasaan politik, dan akses terhadap informasi adalah pihak yang paling diuntungkan. Mereka adalah:
-
Korporasi Skala Besar: Baik itu perusahaan perkebunan kelapa sawit, HTI (Hutan Tanaman Industri), pertambangan, properti, maupun industri pariwisata, korporasi-korporasi ini menjadi penerima manfaat utama dari kebijakan agraria yang longgar atau yang condong pada investasi. Mereka mendapatkan konsesi lahan yang luas, seringkali dalam puluhan hingga ratusan ribu hektar, melalui perizinan yang mudah dan proses akuisisi yang didukung negara. Keuntungan mereka berasal dari produksi komoditas ekspor, ekstraksi sumber daya alam, atau pembangunan infrastruktur yang mendatangkan nilai ekonomi tinggi. Dengan skala operasi yang masif, mereka mampu memobilisasi modal besar, teknologi canggih, dan menguasai rantai pasok global.
-
Investor Domestik dan Asing: Di balik korporasi seringkali ada investor, baik individu maupun institusi keuangan, yang menanamkan modal dengan harapan keuntungan besar. Mereka mencari stabilitas politik, kepastian hukum (yang seringkali diinterpretasikan sebagai kemudahan berinvestasi tanpa banyak hambatan), dan akses murah terhadap sumber daya. Kebijakan deregulasi, insentif pajak, dan jaminan keamanan investasi menjadi daya tarik utama bagi mereka.
-
Elit Politik dan Birokrat: Kebijakan agraria yang kompleks dan seringkali tidak transparan membuka celah bagi praktik korupsi dan kolusi. Pejabat publik atau elit politik dapat mengambil keuntungan dari penerbitan izin, jual-beli lahan, atau bahkan kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor agraria. Alih-alih bertindak sebagai pelayan publik yang melindungi hak-hak rakyat, sebagian dari mereka justru menjadi fasilitator bagi kepentingan modal besar.
-
Negara (dalam Konteks Pendapatan dan Pembangunan Fisik): Pemerintah, dalam kerangka diskursus pembangunan, seringkali melihat investasi agraria sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Pajak, royalti, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor perkebunan, pertambangan, dan industri terkait, menjadi sumber pendapatan penting bagi kas negara. Selain itu, proyek-proyek infrastruktur besar seperti jalan tol, bendungan, bandara, atau kawasan industri yang memerlukan pembebasan lahan, dianggap sebagai simbol kemajuan dan modernisasi. Namun, keuntungan ini seringkali tidak terdistribusi secara merata ke masyarakat luas dan justru memicu kesenjangan.
Mekanisme yang digunakan untuk menguntungkan pihak-pihak ini antara lain adalah: penerbitan HGU (Hak Guna Usaha) atau IUP (Izin Usaha Pertambangan) dalam skala besar; kemudahan pembebasan lahan melalui UU Pengadaan Tanah; kriminalisasi perlawanan masyarakat; serta narasi "pembangunan" yang membenarkan perampasan tanah demi kepentingan umum (yang seringkali diredefinisi secara sempit).
3. Siapa yang Dikorbankan? Kaum Marginal dan Lingkungan
Di sisi lain spektrum, ada kelompok-kelompok yang secara sistematis dikorbankan demi kepentingan akumulasi modal dan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi. Mereka adalah:
-
Petani Kecil dan Petani Gurem: Kelompok ini adalah korban utama dari ekspansi korporasi. Tanah-tanah garapan mereka, yang menjadi satu-satunya sumber penghidupan, seringkali digusur atau dirampas dengan kompensasi yang tidak layak, bahkan tanpa kompensasi sama sekali. Mereka kehilangan akses terhadap lahan produktif, air, dan sumber daya alam lainnya yang selama ini mereka kelola secara tradisional. Akibatnya, mereka terpinggirkan, menjadi buruh tani di tanah mereka sendiri, atau terpaksa urbanisasi tanpa keterampilan yang memadai.
-
Masyarakat Adat: Masyarakat adat memiliki ikatan yang sangat kuat dengan tanah ulayat mereka, yang merupakan basis budaya, spiritual, dan ekonomi. Namun, pengakuan hukum terhadap hak-hak ulayat mereka seringkali sangat lemah atau tidak ada sama sekali. Tanah ulayat mereka kerap diklaim oleh negara sebagai hutan negara atau lahan tidur, kemudian diberikan kepada korporasi dalam bentuk konsesi. Konflik antara masyarakat adat dan perusahaan seringkali berakhir dengan kekerasan, kriminalisasi pemimpin adat, dan hilangnya identitas budaya.
-
Buruh Tani: Meskipun tidak memiliki tanah, buruh tani sangat bergantung pada sektor agraria. Ketika tanah-tanah pertanian beralih fungsi menjadi perkebunan monokultur atau pertambangan, kesempatan kerja mereka menyusut atau digantikan oleh pekerjaan dengan upah rendah dan kondisi kerja yang buruk di sektor formal.
-
Perempuan Pedesaan: Perempuan seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam konflik agraria. Mereka adalah pengelola utama lahan pertanian skala kecil, pencari pangan, dan penopang ekonomi keluarga. Ketika tanah hilang, beban ekonomi dan sosial mereka meningkat drastis, dan mereka seringkali tidak memiliki suara yang cukup dalam proses pengambilan keputusan.
-
Lingkungan Hidup: Kerusakan lingkungan adalah konsekuensi tak terhindarkan dari eksploitasi agraria yang tidak berkelanjutan. Deforestasi besar-besaran untuk perkebunan monokultur atau pertambangan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, erosi tanah, pencemaran air dan udara, serta perubahan iklim. Praktik pertanian intensif dengan pupuk kimia dan pestisida juga merusak kesuburan tanah dan kesehatan ekosistem. Masyarakat lokal yang bergantung pada ekosistem yang sehat untuk air bersih, pangan, dan udara bersih adalah pihak yang paling merasakan dampaknya.
-
Ketahanan Pangan Nasional: Ironisnya, ekspansi perkebunan monokultur yang berorientasi ekspor seringkali mengurangi luas lahan pangan, mengancam kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Ketergantungan pada impor pangan meningkat, dan fluktuasi harga global dapat sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat.
4. Manifestasi Konflik dan Ketidakadilan
Dampak dari politik agraria yang tidak adil termanifestasi dalam berbagai bentuk konflik agraria yang meluas di seluruh Indonesia. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan ribuan kasus konflik agraria yang melibatkan jutaan hektar lahan dan ratusan ribu kepala keluarga. Konflik-konflik ini seringkali diwarnai oleh:
- Kekerasan dan Kriminalisasi: Petani dan masyarakat adat yang berjuang mempertahankan tanah mereka seringkali menghadapi intimidasi, kekerasan, bahkan kriminalisasi dengan tuduhan perambahan atau pengrusakan. Aparat keamanan seringkali berpihak pada korporasi atau pemilik modal.
- Penggusuran Paksa: Ribuan keluarga dipaksa meninggalkan tanah dan rumah mereka demi proyek-proyek "pembangunan" atau ekspansi korporasi, seringkali tanpa ganti rugi yang layak atau bahkan tanpa proses musyawarah yang adil.
- Kerusakan Ekologis Parah: Bekas-bekas tambang yang terbengkalai, sungai yang tercemar, dan hutan yang gundul menjadi saksi bisu dari kerusakan yang tak terpulihkan.
- Peningkatan Kemiskinan dan Ketimpangan: Hilangnya akses terhadap tanah membuat masyarakat pedesaan jatuh ke dalam jurang kemiskinan, memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin.
5. Menuju Politik Agraria yang Adil dan Berkelanjutan
Melihat siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan, jelas bahwa politik agraria di Indonesia saat ini masih jauh dari cita-cita keadilan sosial. Reforma agraria sejati, yang diamanatkan oleh UUPA 1960, belum sepenuhnya terwujud. Ia bukan hanya sekadar redistribusi tanah, tetapi juga reformasi struktural yang mencakup:
- Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah: Mendesak pengakuan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka dan hak-hak petani kecil atas tanah garapan mereka.
- Redistribusi Tanah yang Adil: Mendistribusikan kembali tanah-tanah terlantar, tanah bekas HGU yang habis masa berlakunya, dan tanah-tanah yang dikuasai secara tidak sah kepada petani gurem dan masyarakat tidak bertanah.
- Penguatan Kapasitas Petani: Memberikan dukungan modal, teknologi, dan akses pasar kepada petani kecil agar mereka dapat mengelola tanah secara produktif dan berkelanjutan.
- Penegakan Hukum yang Tegas: Menindak tegas korporasi atau individu yang melakukan pelanggaran agraria, termasuk perampasan tanah dan perusakan lingkungan, serta memastikan keadilan bagi korban konflik agraria.
- Partisipasi Masyarakat: Memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan agraria, mulai dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi.
- Pembangunan Berkelanjutan yang Berpihak Rakyat: Mengubah paradigma pembangunan dari yang ekstraktif dan berorientasi pertumbuhan semata menjadi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat kecil serta lingkungan.
Kesimpulan
Politik agraria adalah cerminan dari struktur kekuasaan dalam sebuah negara. Di Indonesia, ia masih didominasi oleh kepentingan modal besar dan elit politik yang memprioritaskan keuntungan ekonomi jangka pendek di atas keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Akibatnya, kelompok-kelompok paling rentan – petani kecil, masyarakat adat, dan lingkungan – terus menjadi korban.
Mewujudkan politik agraria yang adil dan berkelanjutan adalah tugas mendesak. Ini membutuhkan komitmen politik yang kuat, reformasi kelembagaan, penegakan hukum yang imparsial, dan yang terpenting, pengakuan bahwa tanah bukan hanya komoditas, melainkan fondasi kehidupan, martabat, dan masa depan bangsa. Hanya dengan demikian, narasi pengorbanan dapat digantikan dengan cerita tentang keadilan, kesejahteraan yang merata, dan harmoni antara manusia dan alam. Pertarungan atas tanah adalah pertarungan untuk masa depan Indonesia yang lebih adil dan bermartabat.