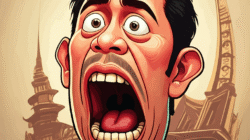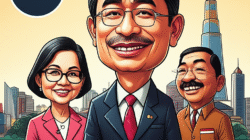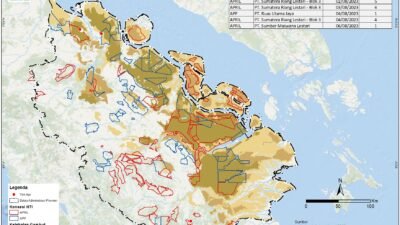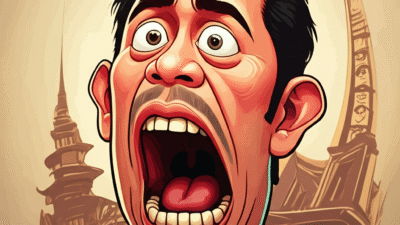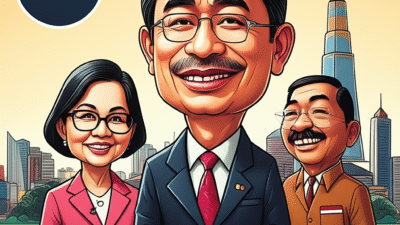Nasionalisme di Persimpangan Jalan: Antara Kekuatan Pembangun dan Bibit Perpecahan di Era Modern
Dalam pusaran globalisasi yang tak henti-hentinya dan kemajuan teknologi yang menghubungkan setiap sudut dunia, sebuah kekuatan kuno kembali menampakkan diri dengan wajah baru: nasionalisme. Konsep yang telah membentuk peta dunia, melahirkan negara-negara, dan memicu revolusi ini kini berada di persimpangan jalan, menunjukkan kembali daya tarik dan bahayanya secara bersamaan. Nasionalisme, pada hakikatnya, adalah ikatan emosional dan ideologis yang mengikat individu pada identitas kolektif sebuah bangsa, mendorong loyalitas, persatuan, dan keinginan untuk memajukan kepentingan nasional. Namun, seperti pedang bermata dua, kekuatannya dapat membangun peradaban atau justru menghancurkannya.
Akar dan Evolusi Nasionalisme: Dari Abad Pencerahan hingga Dekolonisasi
Untuk memahami kompleksitas nasionalisme hari ini, kita perlu menengok kembali ke akarnya. Meskipun sentimen kesukuan atau kedaerahan telah ada sejak lama, nasionalisme sebagai ideologi politik modern mulai menguat pada abad ke-18, didorong oleh gagasan Pencerahan tentang kedaulatan rakyat dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Revolusi Prancis pada tahun 1789 sering dianggap sebagai titik tolak, di mana gagasan "bangsa" menggantikan monarki sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Rakyat tidak lagi hanya menjadi subjek raja, tetapi warga negara yang memiliki ikatan bersama, yaitu bahasa, budaya, sejarah, dan wilayah.
Pada abad ke-19, nasionalisme menyebar ke seluruh Eropa, memicu gerakan penyatuan seperti Italia dan Jerman, serta mendorong pemberontakan melawan kekuasaan imperium. Gelombang kedua nasionalisme muncul pada abad ke-20, khususnya pasca-Perang Dunia II, di mana negara-negara Asia dan Afrika menggunakan semangat nasionalisme untuk membebaskan diri dari penjajahan. Indonesia adalah salah satu contoh nyata bagaimana nasionalisme menjadi motor penggerak perjuangan kemerdekaan, menyatukan beragam etnis dan budaya di bawah satu bendera, satu bahasa, dan satu cita-cita. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 adalah manifestasi awal dari persatuan nasional yang transcenden di atas perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan.
Namun, di samping kisah-kisah heroik tentang pembebasan, sejarah juga mencatat sisi gelap nasionalisme. Nasionalisme yang berlebihan atau eksklusif sering kali memicu konflik, genosida, dan perang dunia. Gagasan tentang superioritas ras atau budaya, seperti yang terjadi di Nazi Jerman, menunjukkan bagaimana nasionalisme dapat dimanipulasi untuk membenarkan kekejaman dan penindasan terhadap "yang lain."
Wajah Positif Nasionalisme: Pilar Pembangunan dan Persatuan
Ketika dihayati secara positif, nasionalisme adalah kekuatan yang tak ternilai. Pertama, ia adalah fondasi identitas kolektif. Dalam dunia yang semakin homogen, nasionalisme membantu suatu bangsa mempertahankan keunikan budaya, bahasa, dan tradisinya. Ia memberikan rasa memiliki, kebanggaan, dan tujuan bersama yang melampaui kepentingan individu. Rasa kebersamaan ini sangat penting untuk stabilitas sosial dan politik.
Kedua, nasionalisme yang sehat mendorong persatuan dan gotong royong. Ketika sebuah negara menghadapi tantangan besar—baik itu bencana alam, krisis ekonomi, atau ancaman eksternal—nasionalisme dapat memobilisasi seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama demi kepentingan yang lebih besar. Contoh paling relevan adalah respons terhadap pandemi COVID-19. Meskipun ada dinamika global, banyak negara mengandalkan semangat nasional untuk mengimplementasikan kebijakan kesehatan, mengembangkan vaksin, dan menjaga solidaritas sosial di tengah isolasi.
Ketiga, nasionalisme dapat menjadi pendorong pembangunan ekonomi dan inovasi. Dengan fokus pada kepentingan nasional, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang melindungi industri dalam negeri, mendorong penelitian dan pengembangan lokal, serta menciptakan lapangan kerja bagi warganya. Kampanye "Cinta Produk Indonesia" adalah contoh bagaimana nasionalisme ekonomi dapat menggerakkan perekonomian domestik dan mengurangi ketergantungan pada barang impor.
Keempat, nasionalisme adalah benteng pertahanan kedaulatan dan integritas wilayah. Setiap bangsa memiliki hak untuk mempertahankan batas-batasnya, sumber daya alamnya, dan sistem politiknya dari campur tangan asing. Rasa nasionalisme yang kuat memastikan bahwa rakyat siap membela negaranya dari segala bentuk ancaman, baik militer, ekonomi, maupun budaya.
Sisi Gelap Nasionalisme: Jurang Konflik dan Eksklusivitas
Namun, batas antara nasionalisme yang sehat dan yang merusak sangat tipis. Ketika nasionalisme berubah menjadi ultranasionalisme atau jingoism, ia mulai menunjukkan sisi gelapnya.
Pertama, nasionalisme yang berlebihan seringkali memicu xenofobia dan diskriminasi. Kecurigaan terhadap orang asing, imigran, atau minoritas yang dianggap "bukan bagian dari kita" dapat berkembang menjadi kebencian dan kekerasan. Di berbagai belahan dunia, kita melihat kebangkitan gerakan-gerakan anti-imigran yang mengklaim melindungi identitas nasional dari "ancaman" luar, padahal seringkali berakar pada ketakutan yang tidak rasional atau kesalahpahaman.
Kedua, nasionalisme eksklusif dapat memperparah konflik internasional. Klaim historis atas wilayah, persaingan sumber daya, atau superioritas budaya dapat dengan mudah Eskalasi menjadi sengketa perbatasan, perang dagang, atau bahkan konflik bersenjata. Dalam kasus terburuk, ini dapat mengarah pada genosida atau pembersihan etnis, di mana kelompok mayoritas menggunakan kekuatan negara untuk menyingkirkan atau menindas minoritas.
Ketiga, nasionalisme seringkali menjadi alat bagi rezim otoriter atau populis. Para pemimpin yang berambisi dapat memanfaatkan sentimen nasionalis untuk menggalang dukungan, membungkam perbedaan pendapat, dan mengonsolidasikan kekuasaan. Dengan mengklaim sebagai satu-satunya pembela kepentingan nasional, mereka dapat menyingkirkan oposisi, membatasi kebebasan sipil, dan mengarahkan perhatian publik dari masalah internal yang sebenarnya.
Keempat, dalam konteks globalisasi, nasionalisme yang proteksionis dapat menghambat kerja sama internasional yang esensial. Tantangan global seperti perubahan iklim, pandemi, terorisme, atau krisis ekonomi membutuhkan solusi kolektif. Jika setiap negara hanya fokus pada kepentingan sempitnya sendiri, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap dunia, maka upaya untuk mengatasi masalah-masalah ini akan menjadi jauh lebih sulit. Penutupan perbatasan, pembatasan perdagangan, dan penolakan kerja sama ilmiah adalah contoh-contoh bagaimana nasionalisme dapat menjadi penghalang bagi kemajuan global.
Nasionalisme di Era Kontemporer: Tantangan Global dan Lokal
Di abad ke-21, nasionalisme menghadapi dinamika yang unik. Kemunculan media sosial dan internet telah mengubah cara narasi nasionalis disebarkan. Informasi, baik yang benar maupun hoaks, dapat menyebar dengan kecepatan kilat, menciptakan "gelembung gema" yang memperkuat pandangan sempit dan memecah belah masyarakat. Populisme, yang seringkali bersekutu erat dengan nasionalisme, memanfaatkan platform ini untuk menyampaikan pesan yang menyederhanakan masalah kompleks menjadi narasi "kita melawan mereka."
Selain itu, ketidaksetaraan ekonomi dan ketidakpuasan terhadap globalisasi juga turut menyuburkan nasionalisme. Ketika sebagian masyarakat merasa ditinggalkan oleh sistem ekonomi global, mereka cenderung mencari perlindungan pada entitas yang paling dekat dengan mereka: negara bangsa. Janji-janji untuk "mengambil kembali kendali" atau "membuat negara hebat kembali" resonansi dengan frustrasi ini.
Di Indonesia, nasionalisme memiliki makna yang sangat mendalam dan multidimensional. Berbeda dengan nasionalisme yang seringkali berakar pada etnisitas di beberapa negara, nasionalisme Indonesia dibangun di atas Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi Tetap Satu). Ini adalah nasionalisme yang inklusif, yang mengakui keragaman sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Namun, tantangan tetap ada. Polarisasi politik, isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), dan penyebaran berita palsu dapat mengancam tenun kebangsaan ini. Penting bagi bangsa Indonesia untuk terus memupuk nasionalisme yang berdasarkan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan keadilan sosial, sebagaimana yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa.
Menavigasi Kompleksitas Nasionalisme: Mencari Keseimbangan
Mengingat kekuatan dan bahaya yang melekat pada nasionalisme, pertanyaan krusialnya adalah bagaimana kita dapat menavigasinya secara bijaksana. Kuncinya terletak pada mencari keseimbangan antara kebanggaan nasional yang sehat dan keterbukaan terhadap dunia.
Pertama, pendidikan memegang peran vital. Generasi muda harus diajarkan tentang sejarah bangsa secara komprehensif, termasuk keberhasilan dan kegagalannya, serta tentang pentingnya nilai-nilai persatuan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Pendidikan juga harus menanamkan kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi nasionalis yang sempit dan memecah belah.
Kedua, promosi nasionalisme sipil (civic nationalism) harus diutamakan. Ini adalah bentuk nasionalisme yang didasarkan pada kesetiaan terhadap nilai-nilai konstitusional, hukum, dan institusi negara, bukan pada etnisitas atau agama. Dalam nasionalisme sipil, siapa pun yang menganut nilai-nilai bersama dan berkontribusi pada masyarakat dianggap sebagai bagian dari bangsa, tanpa memandang latar belakang. Ini sangat relevan dengan konteks Indonesia yang majemuk.
Ketiga, para pemimpin politik memiliki tanggung jawab besar. Mereka harus menggunakan retorika yang menyatukan, bukan memecah belah. Mereka harus mengedepankan kepentingan nasional yang inklusif, bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Ketika berbicara di panggung global, mereka harus mampu menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kebutuhan untuk berkolaborasi dengan negara lain demi mengatasi tantangan bersama.
Keempat, dialog antarbudaya dan antarnegara harus terus didorong. Memahami perspektif bangsa lain, menghargai perbedaan, dan mencari titik temu adalah cara efektif untuk mencegah nasionalisme berubah menjadi permusuhan. Pertukaran pelajar, program budaya, dan diplomasi publik dapat membangun jembatan antar bangsa.
Kesimpulan
Nasionalisme adalah kekuatan abadi dalam sejarah manusia, yang terus membentuk dinamika global dan lokal. Ia adalah manifestasi alami dari kebutuhan manusia akan identitas dan rasa memiliki. Di satu sisi, ia mampu menginspirasi perjuangan kemerdekaan, memupuk persatuan, dan mendorong kemajuan. Di sisi lain, jika dibiarkan tanpa kendali, ia dapat memicu kebencian, konflik, dan kekerasan.
Di era yang semakin terhubung namun juga semakin terpolarisasi ini, tugas kita adalah memastikan bahwa nasionalisme berfungsi sebagai kekuatan konstruktif. Ini berarti memupuk nasionalisme yang inklusif, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal, yang bangga akan identitasnya sendiri tanpa merendahkan orang lain. Dengan demikian, kita dapat memanfaatkan energi positif nasionalisme untuk membangun bangsa yang kuat, adil, dan sejahtera, sekaligus berkontribusi pada perdamaian dan kemajuan dunia. Nasionalisme bukan hanya tentang "kita," tetapi juga tentang bagaimana "kita" berinteraksi dengan "mereka" dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.